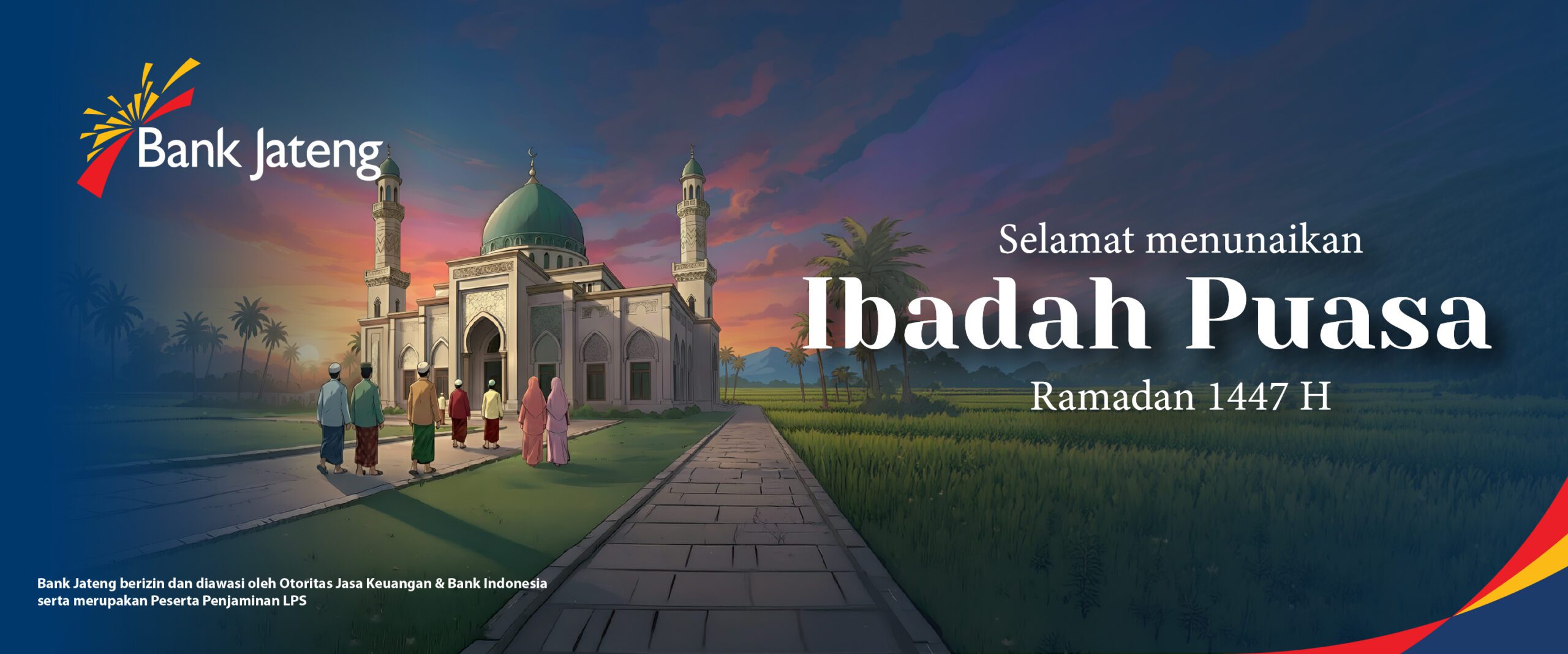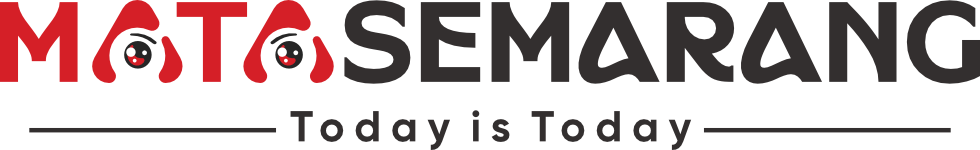MATASEMARANG.COM – Tanggal 27 Mei bukan sekadar penanda dalam kalender nasional. Ia adalah seruan yang menggema dari masa lalu menuju masa depan: Hari Jamu Nasional.
Dicanangkan sebagai hari jamu, pertama kali oleh Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2008, momen ini hadir sebagai perlawanan budaya yang elegan terhadap derasnya arus globalisasi yang kerap mengikis kearifan lokal. Jamu, dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai ramuan herbal, tetapi sebagai pusaka identitas, wujud dari relasi harmoni antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan.
Dalam denyut nadi peradaban Nusantara, jamu telah menjadi sahabat setia sejak abad ke-8 Masehi. Jejak tertulisnya muncul dalam Prasasti Madhawapura dari era Medang Mataram dan semakin diperkaya dalam Serat Centhini (1814) serta Kakawin Nagarakretagama dari zaman Majapahit. Di sana, kita temukan keberadaan acaraki, —para peramu jamu kerajaan—, yang meracik ramuan tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk merawat jiwa, mengukuhkan status sosial, dan mengiringi ritus sakral kerajaan.
Para permaisuri Majapahit, misalnya, dikenal mengonsumsi Jamu Galian Singset, —campuran kencur (Kaempferia galanga), temulawak (Curcuma xanthorrhiza), dan kunyit (Curcuma longa)—, untuk menjaga kecantikan kulit dan stamina tubuh. Sementara itu, Jamu Lempuyang Wangi yang mengombinasikan Zingiber zerumbet dengan madu hutan dan air kelapa muda, digunakan oleh para punggawa istana untuk meningkatkan vitalitas.
Ramuan bukan sekadar campuran tanaman, tetapi bentuk kebijaksanaan ekologis, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan empiris yang diwariskan lintas generasi.
Sebagai negeri megabiodiversitas, Indonesia menyimpan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, di mana sekitar 2.000 di antaranya berpotensi sebagai tanaman obat. Misalnya, temulawak yang kaya akan xanthorrhizol dan kurkuminoid telah terbukti sebagai hepatoprotektor dan antiinflamasi. Ia bahkan diekspor ke Jepang sebagai suplemen pencernaan.
Sambiloto (Andrographis paniculata)—dengan senyawa andrographolide—terbukti menurunkan kolesterol dan menekan replikasi virus, termasuk SARS-CoV-2. Meniran (Phyllanthus niruri) menawarkan efek antivirus dan proteksi vaskular, sementara Kencur telah lama dikenal untuk mengatasi batuk dan meningkatkan stamina.
Namun, jamu tidak boleh tinggal dalam nostalgia. Seperti semboyan “tradisi yang bergerak”, jamu kini melangkah memasuki fase baru: Jamu 6.0. Ini bukan sekadar angka atau branding, melainkan sebuah paradigma transdisipliner yang menyatukan etnofarmakologi, nanoteknologi, imunologi, dan teknologi-omics (genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik). Dalam kerangka ini, tradisi tidak ditinggalkan, tetapi ditransformasikan melalui pendekatan ilmiah dan teknologi presisi.
Salah satu inovasi revolusioner adalah nanoherbalmedicine, —pengolahan senyawa aktif tanaman herbal ke dalam bentuk partikel nano (kurang dari 100 nanometer). Teknologi ini memungkinkan peningkatan bioavailabilitas (kemampuan senyawa untuk diserap tubuh), efektivitas terapi, dan kemampuan menembus penghalang biologis, seperti sawar darah-otak (blood-brain barrier/BBB).
Contohnya, kurkumin nano dari kunyit, kini mampu digunakan dalam terapi neurodegeneratif. seperti alzheimer dan parkinson karena dapat mencapai jaringan otak yang sebelumnya sulit dijangkau.
Manfaat teknologi nano dalam jamu sangat beragam. Pertama, peningkatan efikasi farmakologis. Misalnya, kurkumin dalam bentuk nano memiliki kemampuan diserap tubuh hingga 40 persen lebih tinggi dibanding bentuk konvensional. Kedua, sistem pengiriman target (targeted delivery), menyasar sel atau organ tertentu tanpa merusak jaringan sehat lainnya dan mengurangi toksisitas. Ketiga, stabilitas senyawa bioaktif. Enkapsulasi nanopartikel melindungi senyawa dari degradasi akibat enzim dan cahaya.
Saat ini, berbagai institusi di Indonesia telah mengembangkan produk jamu berbasis nano, seperti nano-sambiloto untuk penguatan imunitas saat pandemi, nano-temulawak untuk kesehatan hati, serta potensi riset gabungan nanoherbal dengan terapi sel punca (stem cell therapy) dalam kedokteran regeneratif.
Lebih jauh lagi, integrasi teknologi-omics telah mengantar kita ke era herbal precision medicine, —pengobatan personal berbasis genetika. Melalui pendekatan herbogenomik, kita dapat memetakan ekspresi gen dari tanaman obat dan memaksimalkan potensi biosintetiknya. Misalnya, temulawak dengan ekspresi gen CYP450 dapat menghasilkan variasi kadar kurkumin yang berbeda-beda. Nutrigenomik memungkinkan kita menyesuaikan jenis dan dosis jamu berdasarkan profil genetik seseorang, sedangkan farmakogenomik memetakan metabolisme senyawa aktif jamu di tubuh pasien, khususnya pada gen seperti CYP2D6 yang memengaruhi efektivitas pengobatan.
Konsep yang kini mengemuka dan sangat menjanjikan adalah Nanoimmunoherbogenomics, —perpaduan tiga pilar utama: nanoteknologi, imunologi, dan teknologi-omics untuk pengembangan jamu berbasis bukti (evidence-based). Ini adalah titik temu antara laboratorium canggih dengan pawon nenek di desa. Sebuah jembatan antara kecanggihan AI (artificial intelligence) dengan intuisi empiris para empu jamu. Dalam konsep ini, jamu bukan lagi dianggap sebagai alternatif, melainkan sebagai pelengkap setara dalam sistem kesehatan modern (complementary medicine).
Digitalisasi menjadi sayap bagi jamu untuk terbang lebih tinggi. Penggunaan blockchain dalam pelacakan rantai pasok bahan baku jamu menjamin transparansi dan keaslian produk. Aplikasi mobile memungkinkan personalisasi racikan jamu berdasarkan gejala, data genetik, hingga rekam jejak konsumsi harian pengguna. Di sisi promosi, platform e-commerce dan media sosial seperti TikTok menjadi panggung baru bagi UMKM jamu untuk menjangkau pasar global. Bahkan, simulasi 3D dan metaverse dapat menghadirkan “klinik jamu virtual” di mana pengguna bisa berkonsultasi langsung dengan herbalis dan menyaksikan proses pembuatan jamu secara imersif.
Dalam strategi internasionalisasi, penting untuk mendorong sertifikasi jamu sebagai Complementary and Alternative Medicine (CAM) di WHO, FDA (Amerika Serikat), dan EMA (Eropa). Kerja sama riset dengan universitas dunia, seperti Taipei Medical University, membuka ruang kolaboratif dalam pengembangan nanoimmunoherbogenomics. Festival jamu internasional, pameran budaya, hingga promosi melalui Indonesian Cultural Center dapat memperkuat diplomasi kesehatan berbasis warisan budaya.
Namun, transformasi ini tidak akan sempurna tanpa pemberdayaan komunitas akar rumput. Perempuan, yang secara historis memegang peran sebagai penjaga tradisi jamu, perlu diberdayakan sebagai pelatih, inovator, dan duta jamu digital. Pelatihan pembuatan jamu nano berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh PKK atau Dharma Wanita, dapat melahirkan gelombang baru pelaku industri herbal mikro.
Konsep Desa Wisata Jamu dengan slogan “One Village One Jamu” menjadi inspirasi nyata. Setiap desa mengembangkan produk unggulan berbasis kekayaan lokal, misalnya: Desa Kencur di Bali, Desa Temulawak di Jawa Tengah, Desa Pegagan di Jawa Barat. Di sana, wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga ikut meracik jamu, belajar tentang fitokimia, dan membawa pulang pengalaman transformatif.
Organisasi profesi seperti PDPOTJI (Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia) berperan penting dalam membumikan riset ilmiah, penulisan buku, dan memfasilitasi diskusi publik tentang jamu di ranah kesehatan modern. Webinar, publikasi ilmiah, hingga futuristic outreach ke kampus, sekolah, pesantren menjadi sarana penyebaran pemahaman yang inklusif.
Jamu 6.0 bukan sekadar terminologi. Ia adalah narasi masa depan: narasi tentang bangsa yang tidak melupakan akarnya, namun juga tidak takut menjangkau langit. Di sinilah jamu bukan lagi semata “obat rakyat”, tetapi penanda peradaban—di mana kearifan tradisional dipadukan dengan terobosan teknologi, menghasilkan solusi kesehatan yang lebih holistik, adaptif, dan berkelanjutan.
Seperti pepatah Jawa menyatakan, “Jamu iku ora mung tamba, nanging ugungane budaya”—jamu bukan hanya penawar penyakit, tetapi jiwa dari kebudayaan itu sendiri. Maka di tengah zaman yang serba digital, mari kita genggam kembali warisan ini dengan cara yang baru—tanpa kehilangan jati diri. (Antara)
*)Penulis: Dokter Dito Anurogo MSc PhD, inisiator Nanoimmunoherbogenomics, alumnus PhD dari IPCTRM TMU Taiwan, dosen FKIK Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, peneliti di Institut Molekul Indonesia, anggota PDPOTJI
Jamu 6.0: Lebih dari Sekadar Kolaborasi Tradisi dan Teknologi